Bogor Times- Membaca kasus Ferdinan Hutahaean (FH) akan lebih menarik jika menganalisanya dari sudut pandang filsafat analitik Wittgenstein. Menarik karena dengan analisa ini akan terlihat, apakah Ferdinan Hutahaean ini korban, target, atau tumbal.
Sebagai pemantik wacana, saya kutipkan beberapa substansi filsafat analitiknya Wittgenstein.
Mustahil untuk membangun dan menerapkan sebuah tata aturan permainan bahasa tunggal dan umum. Inilah prinsip utama pemikiran Wittgenstein.
Pemikiran Wittgenstein bisa terlihat dalam sebuah pernyataannya: “Makna sebuah kata tergantung penggunaannya dalam sebuah kalimat, makna sebuah kalimat tergantung penggunaannya dalam sebuah bahasa, dan makna sebuah bahasa tergantung penggunaanya dalam sebuah kehidupan.”
Baca Juga: RANU LIMUSNUNGGAL : VISI DAN MISI KAMI ADALAH MENJADIKAN NU BERMANFAAT BAGI WARGA SEKITAR
Konteks inilah sebenarnya padanan maksud yang dibangun oleh Wittgenstein dengan istilah tata permainan bahasa itu. Setiap makna kata dan kalimat sama sekali tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melandasi penggunaannya dalam kehidupan pengucapnya.
Kata kiri, misalnya, jika konteks penggunaannya dilakukan di atas kendaraan umum, maka ia bermakna “stop, berhenti”. Jika ia digunakan dalam konteks sebuah diskusi tentang relasi kapitalisme dan komunisme, ia menunjuk pada makna “komunisme”. Jika ia dipakai dalam konteks studi Islam, ia bermakna “kaum liberalis” yang berhadapan dengan kaum tradisional (kanan). Jika ia dipakai dalam konteks rambu-rambu lalu lintas, ia bisa berarti “belok kiri”. Dan seterusnya.
Misal lain, kata “rumah”. Jika konteks penggunaannya menunjuk pada bangunan, maka ia berarti sebuah “tempat tinggal”. Jika digunakan dalam konteks kebudayaan, ia berarti “akar budaya”. Jika digunakan dalam konteks politik, ia berarti “partai politik”.Danseterusnya.
Baca Juga: PMII Serius Kawal Dugaan Kasus Maling Uang Rakyat Program Sembako/BPNT
Belum lagi bila sebuah kata dipergunakan dalam konteks formal atau tidak. Kata “aku”, misalnya, jika digunakan dalam konteks non-formal, keseharian atau persahabatan, menghadirkan makna yang dekat, akrab, dan intim. Tapi jika kata “aku” digunakan dalam konteks formal, misal dalam sebuah seminar, jelas ia akan menimbulkan kesan tidak sopan, kurang pas, dan bahkan tidak menyenangkan. Karena itu, konteks formal dan non-formal ini pun harus diperhatikan dengan baik tata aturan permainannya, tidak boleh dicampur-adukkan, atau diabaikan, karena akan memicu kerancuan makna.
Filsafat ala Wittgenstein ini yang mampu dipahami sekaligus dimainkan oleh beberapa kelompok ditengah maraknya politik identitas.
Politik identitas rentan dijadikan alat untuk kepentingan pragmatis. Lebih-lebih jika didahului dengan isu-isu yang sensitif.
Diantara sekian banya isu, agama menjadi paling seksi. Sebab, ketika isu agama dimunculkan, maka emosi massa akan mudah tergerakkan walaupun belum terverifikasi kebenaran isu tersebut.
Inilah salah saktu kekuatan gerakan 212 yang mengangkat isu penistaan agama walaupun belakangan fakta yang sebenarnya diangkat oleh Buni Yani sang pengunggah vidio editan Ahok yang menjadi pemicunya.











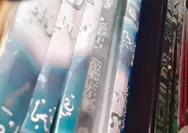







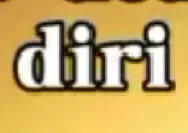




Artikel Terkait
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prediksi Hari ini Berpotensi Hujan
Tak Pernah Berharap, Mensos Risma Masuk Daftar Gubernur DKI Jakarta
Awas, Penipuan Mengatas Namakan Aplikasi Pinjol
PMII Serius Kawal Dugaan Kasus Maling Uang Rakyat Program Sembako/BPNT
RANU LIMUSNUNGGAL : VISI DAN MISI KAMI ADALAH MENJADIKAN NU BERMANFAAT BAGI WARGA SEKITAR